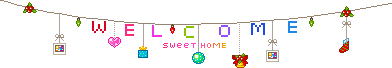
More About Me
Kelinci,Gemini,ENTJ
Kholeris,Sanguinis
Jakarta,Indonesia
Buku,musik,film
Coklat,es krim,salad buah
Gone with the wind,
Topeng Kaca, Shogun, Taiko,
Chicken Soup For The Soul
Legenda Naga
BPA Free seller
Ken n Mom Shop on Facebook
Chit Chat Box
Free shoutbox @ ShoutMix
Other Blogs
Links
Milis
Friends
Afien - Michelle & marco
Alice
Amey - Zio
Andrew
Anita - Davian
Apple - Evelyne
Ariany - Marv
Arman
C
Caroline - Ryo, Aubrey & Matthew
Christine - Jeremy & nicole
Debby
Deeva
Dessy
Dian
Dini - Zeeva
Esther
Febby - Timmy & Nick
Fen - Ken & Kev
Ferlin - Kiefe
Flora - Grace
Ikho - Adelle
Ina
Ingrid - Bryan
Intan - Johanes
Jayadi family
Jesslyn
Limmy - Dhika
Mei
Melanie
Montan - Aurel
Natalie - Dexter
Nathan
Nicholas
Orlando
Piabo - Ethan
Pitshu
Pucca
Retha
Ria - Calvin
Rosa
Sakura Lady
Salma
Sam & Ase
Santi - Michael
Selvi - Brandon
Setia - Jonathan
Sharah - Lila & Nawal
Shawn
Shierly
Sofie - Toriq
Vera - Wilbert
Vivie - Patrick
Wendy - Bryan
Wie
Wiwin
Yanti - Callis
Yulia - Fang2
Yulian - Jeslyn
Yolan - Michelle
Archives
- October 2003
- November 2003
- January 2004
- February 2004
- March 2004
- April 2004
- May 2004
- June 2004
- July 2004
- August 2004
- September 2004
- October 2004
- November 2004
- December 2004
- January 2005
- February 2005
- May 2005
- June 2005
- July 2005
- November 2005
- January 2006
- February 2006
- March 2006
- April 2006
- May 2006
- June 2006
- July 2006
- August 2006
- September 2006
- October 2006
- November 2006
- December 2006
- January 2007
- February 2007
- March 2007
- April 2007
- May 2007
- June 2007
- July 2007
- August 2007
- September 2007
- October 2007
- November 2007
- December 2007
- January 2008
- February 2008
- March 2008
- April 2008
- May 2008
- June 2008
- July 2008
- August 2008
- September 2008
- October 2008
- November 2008
- December 2008
- January 2009
- February 2009
- March 2009
- April 2009
- May 2009
Previous entries
Friend's Update
Wednesday, August 01, 2007,3:41:00 PM
Diagnosis Anak Jenius
Oleh: Julia Maria van Tiel
Republika, 5 Maret 2002
Menyimak tulisan tentang masalah autisme dalam dua terbitan Republika (25
dan 26 Februari 2002), buat saya sangat menarik sekaligus menimbulkan
greget tersendiri. Bagaimana tidak dalam satu tulisan bisa menampilkan
sebuah polemik tentang penyebab autisme, satu ahli mengatakan penyebabnya
belum diketahui, kemungkinan besar faktor genetik membawa peranan; tetapi
ahli lain mengatakan banyak faktor sebagai penyebab baik saat kehamilan
maupun pasca kelahiran.
Satu ahli mengatakan terapinya adalah terapi perilaku yang disesuaikan
dengan kebutuhan, dan dalam menghadapi konflik antar-diagnotician tentang
label dan kekhawatiran adanya overdiagnosis, ia lebih memilih jalan
tengah, bahwa kita tidak perlu pusing dengan label, tetapi berbagai
penyimpangan maupun kelainan pertumbuhan dan perkembangan hendaknya
ditangani sedini-dininya. Sementara itu ahli lain tetap mengharapkan
penggunaan label autisme dengan mengatakan bahwa masyarakat hendaknya
jangan menutup mata jika anaknya mengalami gangguan autisme.
Autisme yang merebak saat ini--di dunia maupun Indonesia--telah menjadi
momok buat semua orangtua. Bagaimana tidak jika isunya mengatakan bahwa di
Indonesia saja mencapai 1:150 anak mengalami hal ini, dan tidak akan
sembuh pula. Isu vaksin sebagai biang keladi pun menjadi hantu yang cukup
mengerikan. Bagi orangtua yang anaknya terstempel label autisme (yang
tidak mungkin sembuh itu), serta merta mengalami kepanikan dan diterima
oleh berbagai terapi alternatif komersial baik radikal maupun tidak, serta
belum jelas hasilnya.
Ironisnya seperti yang diakui ahli dalam tulisan itu, masalah diagnosis
autisme sendiri masih diperdebatkan oleh para dokter sendiri. Ada yang
mengatakan betul autisme, atau hanya hiperaktif saja, bahkan bukan
apa-apa, saat menghadapi suatu pasien yang sama.
Lalu bagaimana kita mampu memilih bentuk terapi yang benar, jika kausa dan
diagnosisnya masih menjadi perdebatan?
Sementara itu, para orangtua sangat resah ingin segera mengerti tentang
anaknya itu, agar mampu menjadikan anak yang mandiri. Label autisme
(sekalipun masih kontraversial, dalam spektrum, sindrom, berat-ringan,
autistik features) membawanya mengembara mencari-cari, seperti apakah
kelak anakku ini? Ternyata yang ketemu, figur Rain Man dalam sebuah film
yang dimainkan Dustin Hoffman--seorang autis savant yang idiot dengan
kemampuan memori verbal dan memori visual yang hebat sehingga mampu
bermain perkalian sampai berdigit-digit tanpa kalkulator. Atau bertemu
pada figur asperger yang mampu menjadi seorang doktor sekalipun, tetapi
mengalami gangguan berkomunikasi dengan orang lain. Padahal tipe autisme
asperger ini pada waktu balita tidak mengalami keterlambatan bicara.
Disangkanya kelak anaknya akan seperti itu, padahal autis savant hanya
berjumlah 10 persen dari autisme infantil yang mental retarded, dan
asperger yang ber IQ tinggi hanya berjumlah tiga persen saja dari
kelompoknya.
Saya bersama beberapa rekan dokter dan psikolog secara sukarela dan
nirlaba meluangkan waktu membina mailinglist anak berbakat. Mencari
informasi ke seluruh dunia dan menyampaikan ke tanah air. Kami dan para
anggota mailing list adalah para orangtua yang mempunyai anak- anak yang
senasib, menyadari bahwa kami adalah kelompok yang terjepit, dan
kebingungan. Bagaimana tidak, di antara para anggota kami, anak- anaknya
pernah mendapat stempel bermacam-macam, bahkan ada yang sampai 5 jenis
diagnosis. Atau jika anak itu ternyata sudah mampu bicara dengan baik,
diagnosis pun berubah, tadinya autisme berubah menjadi ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder). Atau karena sangat pintar, ia
terdiagnosis sebagai autis savant, ataupun autis asperger. Sesuatu hal
yang tidaklah mungkin, karena autisme sulit mengalami pencapaian taraf
perkembangan yang drastis macam anak-anak kami, autisme tidak kreatif dan
tidak analistis. ADHD sendiri tidak pernah mengalami keterlambatan bicara.
Terapi psikotropika pun dari risperdal bagi autisme berubah kepada ritalin
bagi ADHD. Atau bahkan ada yang sekaligus risperdal dan ritalin. Atau pagi
harus menelan risperdal dan sore menelan prozac. Belum lagi berbagai
terapi alternatif sampingan yang bukan saja menguras kantung, tetapi juga
emosi. Pencarian sekolah pun menjadi dilema, mereka ditolak dimana-mana,
mulai dari sekolah luar biasa hingga sekolah biasa, karena dianggap
bergangguan jiwa.
Air mata yang tumpah bertahun-tahun dari para orangtua itu, yang selalu
dituding sebagai orangtua yang denial terhadap diagnosis autisme anaknya,
telah menyadarkan kami, saat anak-anak ini telah mampu menjalani test IQ
di usianya yang ke lima atau ke enam. Mereka ternyata adalah anak-anak
exceptional gifted (berbakat dengan IQ yang sangat tinggi yang dapat
dikatakan sebagai anak-anak jenius). Anak- anak ini mengalami perkembangan
yang dyssynchonie yang berakibat pada berbagai perkembangannya tidak sama
dengan anak normal lainnya, sebagiannya mengalami perkembangan bersindrom
autisme dan sebagian lagi bersindrom ADHD. Perkembangan dyssynchronie pada
anak exceptional gifted ini dinyatakan tidak patologis tetapi sebagai
karakteristik, pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog Perancis
tahun 1971, dan kini telah diterima di banyak negara di daratan Eropa. Di
Belanda kondisi dyssynchronie ini dikenal sebagai kinderen met onwikkeling
voorsprong (mengalami loncatan perkembangan, tetapi tertinggal di beberapa
domain perkembangan), dan telah diterima secara mapan oleh semua profesi
serta telah diajarkan di semua pendidikan yang berkaitan dengan tumbuh
kembang anak-anak.
Di Amerika dikenal sebagai gifted with learning disabilities, karena
ketidak sinkronannya itu menyebabkan berbagai gangguan penerimaan
pengajaran dan perkembangan sosial-emosional. Terminologi gifted with
learning disabilities ini juga ternyata membawa dilema pada anak-anak ini,
karena learning disabilities-nya inilah mereka lalu menjadi bulan-bulanan
sasaran berbagai terapi alternatif, termasuk terapi nutrisi, megavitamin
dan herbalis yang kini makin menjamur. Apalagi anak-anak ini kelompok anak
yang mengalami biological disorder, seperti alergi dan gangguan
metabolisme.
Kesulitan mendeteksi balita calon jenius ini juga disebabkan karena gejala
yang dihadirkan anak-anak ini sangat mirip dengan berbagai gangguan mental
lainnya. Begitu sulitnya untuk menegakkan diagnosis, maka banyak kalangan
yang berpendapat bahwa, apa pun anak itu jadinya kelak, kalau balitanya
menunjukkan penyimpangan perkembangan pokoknya sebaiknya diterapi saja.
Karena gejalanya mirip-mirip dengan autisme ataupun ADHD. Maka tidak ayal
pula kelompok kami menjadi bersitegang dengan kelompok yang mempertahankan
diagnosis autisme ataupun gangguan mental lainnya. Karena menurutnya
dikhawatirkan kelak masyarakat menyangka bahwa yang mempunyai gejala autis
itu adalah anak jenius, lalu tidak mau membawa anaknya ke dokter,
sebagaimana yang banyak tersebar saat ini dalam masyarakat.
Terlibatnya anak-anak jenius ini dalam berbagai diagnosis gangguan mental
akhir-akhir ini karena adanya perubahan sistem diagnosis yang digunakan di
berbagai belahan dunia pada sepuluh tahun terakhir. Bahkan banyak
publikasi pula di tanah air yang mengatakan bahwa Einstein, Michelangelo,
Thomas Alfa Edison, yang kita kenal selama ini sebagai orang jenius, kini
dinyatakan sebagai orang-orang autis. Publikasi ini tentu saja membuat
giris kelompok jenius. Bahkan ada pula publikasi seorang pakar terapi
autisme mengatakan bahwa jika autis diterapi dan sembuh maka ia akan
menjadi jenius (Media Indonesia, 7/9/2001).
Sekalipun anak-anak ini masa balitanya mempunyai perkembangan bersindrom
autisme ataupun ADHD, tetapi mereka tidak sama dengan autisme ataupun
ADHD. Betul gejala mereka berada di garis antara normal dan tidak normal.
Tapi bukan berarti grey area ini kemudian ditarik menjadi autisme ataupun
ADHD dan menerima berbagai terapi yang sama dengan autisme atau ADHD.
Sekalipun mempunyai gejala perilaku yang mirip-mirip, tetapi
psiko-neurobiologis mereka amat berbeda dengan autis/ADHD.
Sayangnya ilmu tentang anak-anak yang exceptional gifted (jenius) ini di
Indonesia tidak populer, baik dilingkungan psikolog dan pedagog sendiri
sebagai profesi yang bertanggung jawab dalam bimbingan dan pengembangan
anak-anak ini, ataupun juga dilingkungan dokter anak yang bertanggung
jawab dalam mengawasi tumbuh kembang anak-anak balita, serta di lingkungan
psikiater yang seharusnya mampu memilah mana yang disorder dan mana yang
tidak disorder. Budaya kesehatan pun yang tidak membiasakan pemantauan
balita secara detil, tidak mendukung terdeteksinya anak-anak ini sebagai
anak exceptional gifted yang mengalami dyssynchronie perkembangan dan
membutuhkan perhatian ekstra, dukungan lingkungan, bimbingan sebagaimana
yang dibutuhkan, serta pengembangan berbagai aspek yang tertinggal,
mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, dan mengeliminasi berbagai
kekurangannya, agar ia mampu hidup senormal mungkin dan berprestasi
seoptimal mungkin.
Apa yang kita ketahui selama ini tentang anak berbakat adalah anak yang
baik-baik saja, tidak mengalami ketidakseimbangan perkembangan, serta
dinyatakan tidak disorder. Karena itu, tidak pernah diperhatikan oleh
semua profesi, mereka terlupakan, bahkan terdepak dari diagnosis satu ke
diagnosis lainnya. Anak dan orangtua mengalami duka lara yang luar biasa.
Padahal anak-anak ini berjumlah dua persen dari anak yang lahir ke dunia.
Suatu jumlah yang sangat besar.
Apa yang bisa diharapkan saat ini adalah agar para profesional
menghentikan perdebatan dan selisih pendapat mereka, bersama-sama
mempelajari serta membuat kesepakatan, serta bersatunya berbagai ikatan
profesi yang bertanggung jawab pada tumbuh kembang, bimbingan dan
pendidikan anak-anak ini, seperti dokter anak, psikolog, dan pedagog.
Republika, Selasa, 05 Maret 2002
posted by Julia van Tiel @ 2:46 AM
Republika, 5 Maret 2002
Menyimak tulisan tentang masalah autisme dalam dua terbitan Republika (25
dan 26 Februari 2002), buat saya sangat menarik sekaligus menimbulkan
greget tersendiri. Bagaimana tidak dalam satu tulisan bisa menampilkan
sebuah polemik tentang penyebab autisme, satu ahli mengatakan penyebabnya
belum diketahui, kemungkinan besar faktor genetik membawa peranan; tetapi
ahli lain mengatakan banyak faktor sebagai penyebab baik saat kehamilan
maupun pasca kelahiran.
Satu ahli mengatakan terapinya adalah terapi perilaku yang disesuaikan
dengan kebutuhan, dan dalam menghadapi konflik antar-diagnotician tentang
label dan kekhawatiran adanya overdiagnosis, ia lebih memilih jalan
tengah, bahwa kita tidak perlu pusing dengan label, tetapi berbagai
penyimpangan maupun kelainan pertumbuhan dan perkembangan hendaknya
ditangani sedini-dininya. Sementara itu ahli lain tetap mengharapkan
penggunaan label autisme dengan mengatakan bahwa masyarakat hendaknya
jangan menutup mata jika anaknya mengalami gangguan autisme.
Autisme yang merebak saat ini--di dunia maupun Indonesia--telah menjadi
momok buat semua orangtua. Bagaimana tidak jika isunya mengatakan bahwa di
Indonesia saja mencapai 1:150 anak mengalami hal ini, dan tidak akan
sembuh pula. Isu vaksin sebagai biang keladi pun menjadi hantu yang cukup
mengerikan. Bagi orangtua yang anaknya terstempel label autisme (yang
tidak mungkin sembuh itu), serta merta mengalami kepanikan dan diterima
oleh berbagai terapi alternatif komersial baik radikal maupun tidak, serta
belum jelas hasilnya.
Ironisnya seperti yang diakui ahli dalam tulisan itu, masalah diagnosis
autisme sendiri masih diperdebatkan oleh para dokter sendiri. Ada yang
mengatakan betul autisme, atau hanya hiperaktif saja, bahkan bukan
apa-apa, saat menghadapi suatu pasien yang sama.
Lalu bagaimana kita mampu memilih bentuk terapi yang benar, jika kausa dan
diagnosisnya masih menjadi perdebatan?
Sementara itu, para orangtua sangat resah ingin segera mengerti tentang
anaknya itu, agar mampu menjadikan anak yang mandiri. Label autisme
(sekalipun masih kontraversial, dalam spektrum, sindrom, berat-ringan,
autistik features) membawanya mengembara mencari-cari, seperti apakah
kelak anakku ini? Ternyata yang ketemu, figur Rain Man dalam sebuah film
yang dimainkan Dustin Hoffman--seorang autis savant yang idiot dengan
kemampuan memori verbal dan memori visual yang hebat sehingga mampu
bermain perkalian sampai berdigit-digit tanpa kalkulator. Atau bertemu
pada figur asperger yang mampu menjadi seorang doktor sekalipun, tetapi
mengalami gangguan berkomunikasi dengan orang lain. Padahal tipe autisme
asperger ini pada waktu balita tidak mengalami keterlambatan bicara.
Disangkanya kelak anaknya akan seperti itu, padahal autis savant hanya
berjumlah 10 persen dari autisme infantil yang mental retarded, dan
asperger yang ber IQ tinggi hanya berjumlah tiga persen saja dari
kelompoknya.
Saya bersama beberapa rekan dokter dan psikolog secara sukarela dan
nirlaba meluangkan waktu membina mailinglist anak berbakat. Mencari
informasi ke seluruh dunia dan menyampaikan ke tanah air. Kami dan para
anggota mailing list adalah para orangtua yang mempunyai anak- anak yang
senasib, menyadari bahwa kami adalah kelompok yang terjepit, dan
kebingungan. Bagaimana tidak, di antara para anggota kami, anak- anaknya
pernah mendapat stempel bermacam-macam, bahkan ada yang sampai 5 jenis
diagnosis. Atau jika anak itu ternyata sudah mampu bicara dengan baik,
diagnosis pun berubah, tadinya autisme berubah menjadi ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder). Atau karena sangat pintar, ia
terdiagnosis sebagai autis savant, ataupun autis asperger. Sesuatu hal
yang tidaklah mungkin, karena autisme sulit mengalami pencapaian taraf
perkembangan yang drastis macam anak-anak kami, autisme tidak kreatif dan
tidak analistis. ADHD sendiri tidak pernah mengalami keterlambatan bicara.
Terapi psikotropika pun dari risperdal bagi autisme berubah kepada ritalin
bagi ADHD. Atau bahkan ada yang sekaligus risperdal dan ritalin. Atau pagi
harus menelan risperdal dan sore menelan prozac. Belum lagi berbagai
terapi alternatif sampingan yang bukan saja menguras kantung, tetapi juga
emosi. Pencarian sekolah pun menjadi dilema, mereka ditolak dimana-mana,
mulai dari sekolah luar biasa hingga sekolah biasa, karena dianggap
bergangguan jiwa.
Air mata yang tumpah bertahun-tahun dari para orangtua itu, yang selalu
dituding sebagai orangtua yang denial terhadap diagnosis autisme anaknya,
telah menyadarkan kami, saat anak-anak ini telah mampu menjalani test IQ
di usianya yang ke lima atau ke enam. Mereka ternyata adalah anak-anak
exceptional gifted (berbakat dengan IQ yang sangat tinggi yang dapat
dikatakan sebagai anak-anak jenius). Anak- anak ini mengalami perkembangan
yang dyssynchonie yang berakibat pada berbagai perkembangannya tidak sama
dengan anak normal lainnya, sebagiannya mengalami perkembangan bersindrom
autisme dan sebagian lagi bersindrom ADHD. Perkembangan dyssynchronie pada
anak exceptional gifted ini dinyatakan tidak patologis tetapi sebagai
karakteristik, pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog Perancis
tahun 1971, dan kini telah diterima di banyak negara di daratan Eropa. Di
Belanda kondisi dyssynchronie ini dikenal sebagai kinderen met onwikkeling
voorsprong (mengalami loncatan perkembangan, tetapi tertinggal di beberapa
domain perkembangan), dan telah diterima secara mapan oleh semua profesi
serta telah diajarkan di semua pendidikan yang berkaitan dengan tumbuh
kembang anak-anak.
Di Amerika dikenal sebagai gifted with learning disabilities, karena
ketidak sinkronannya itu menyebabkan berbagai gangguan penerimaan
pengajaran dan perkembangan sosial-emosional. Terminologi gifted with
learning disabilities ini juga ternyata membawa dilema pada anak-anak ini,
karena learning disabilities-nya inilah mereka lalu menjadi bulan-bulanan
sasaran berbagai terapi alternatif, termasuk terapi nutrisi, megavitamin
dan herbalis yang kini makin menjamur. Apalagi anak-anak ini kelompok anak
yang mengalami biological disorder, seperti alergi dan gangguan
metabolisme.
Kesulitan mendeteksi balita calon jenius ini juga disebabkan karena gejala
yang dihadirkan anak-anak ini sangat mirip dengan berbagai gangguan mental
lainnya. Begitu sulitnya untuk menegakkan diagnosis, maka banyak kalangan
yang berpendapat bahwa, apa pun anak itu jadinya kelak, kalau balitanya
menunjukkan penyimpangan perkembangan pokoknya sebaiknya diterapi saja.
Karena gejalanya mirip-mirip dengan autisme ataupun ADHD. Maka tidak ayal
pula kelompok kami menjadi bersitegang dengan kelompok yang mempertahankan
diagnosis autisme ataupun gangguan mental lainnya. Karena menurutnya
dikhawatirkan kelak masyarakat menyangka bahwa yang mempunyai gejala autis
itu adalah anak jenius, lalu tidak mau membawa anaknya ke dokter,
sebagaimana yang banyak tersebar saat ini dalam masyarakat.
Terlibatnya anak-anak jenius ini dalam berbagai diagnosis gangguan mental
akhir-akhir ini karena adanya perubahan sistem diagnosis yang digunakan di
berbagai belahan dunia pada sepuluh tahun terakhir. Bahkan banyak
publikasi pula di tanah air yang mengatakan bahwa Einstein, Michelangelo,
Thomas Alfa Edison, yang kita kenal selama ini sebagai orang jenius, kini
dinyatakan sebagai orang-orang autis. Publikasi ini tentu saja membuat
giris kelompok jenius. Bahkan ada pula publikasi seorang pakar terapi
autisme mengatakan bahwa jika autis diterapi dan sembuh maka ia akan
menjadi jenius (Media Indonesia, 7/9/2001).
Sekalipun anak-anak ini masa balitanya mempunyai perkembangan bersindrom
autisme ataupun ADHD, tetapi mereka tidak sama dengan autisme ataupun
ADHD. Betul gejala mereka berada di garis antara normal dan tidak normal.
Tapi bukan berarti grey area ini kemudian ditarik menjadi autisme ataupun
ADHD dan menerima berbagai terapi yang sama dengan autisme atau ADHD.
Sekalipun mempunyai gejala perilaku yang mirip-mirip, tetapi
psiko-neurobiologis mereka amat berbeda dengan autis/ADHD.
Sayangnya ilmu tentang anak-anak yang exceptional gifted (jenius) ini di
Indonesia tidak populer, baik dilingkungan psikolog dan pedagog sendiri
sebagai profesi yang bertanggung jawab dalam bimbingan dan pengembangan
anak-anak ini, ataupun juga dilingkungan dokter anak yang bertanggung
jawab dalam mengawasi tumbuh kembang anak-anak balita, serta di lingkungan
psikiater yang seharusnya mampu memilah mana yang disorder dan mana yang
tidak disorder. Budaya kesehatan pun yang tidak membiasakan pemantauan
balita secara detil, tidak mendukung terdeteksinya anak-anak ini sebagai
anak exceptional gifted yang mengalami dyssynchronie perkembangan dan
membutuhkan perhatian ekstra, dukungan lingkungan, bimbingan sebagaimana
yang dibutuhkan, serta pengembangan berbagai aspek yang tertinggal,
mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, dan mengeliminasi berbagai
kekurangannya, agar ia mampu hidup senormal mungkin dan berprestasi
seoptimal mungkin.
Apa yang kita ketahui selama ini tentang anak berbakat adalah anak yang
baik-baik saja, tidak mengalami ketidakseimbangan perkembangan, serta
dinyatakan tidak disorder. Karena itu, tidak pernah diperhatikan oleh
semua profesi, mereka terlupakan, bahkan terdepak dari diagnosis satu ke
diagnosis lainnya. Anak dan orangtua mengalami duka lara yang luar biasa.
Padahal anak-anak ini berjumlah dua persen dari anak yang lahir ke dunia.
Suatu jumlah yang sangat besar.
Apa yang bisa diharapkan saat ini adalah agar para profesional
menghentikan perdebatan dan selisih pendapat mereka, bersama-sama
mempelajari serta membuat kesepakatan, serta bersatunya berbagai ikatan
profesi yang bertanggung jawab pada tumbuh kembang, bimbingan dan
pendidikan anak-anak ini, seperti dokter anak, psikolog, dan pedagog.
Republika, Selasa, 05 Maret 2002
posted by Julia van Tiel @ 2:46 AM
Labels: Article

